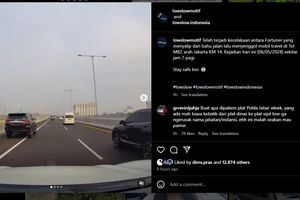Belahan Jiwa Wartawan Tiga Zaman
ST SULARTO
• Judul:
Dibantu salah satu cucunya, Alma Fanniya Idral, ia mengedit terakhir naskah, menentukan urutan penempatan tiga Pengantar: Jakob Oetama, Toeti Heraty, dan Sabam Siagian. ”Jakob dan Sabam, bagus saya tahu. Toeti kan filosof,” komentarnya ketika terbaring sakit di RS Harapan Kita.
Rosihan Anwar sudah memenuhi janji yang dia katakan kepada beberapa teman pada saat makan malam peluncuran bukunya, Petite Histoire jilid 4, Oktober 2010. Namun, kehendak Sang Khalik tidak bisa dilawan. Haji Rosihan Anwar (10 Mei 1922-14 April 2011) meninggal beberapa hari sebelum buku ini terbit.
Membaca buku ini ibarat membaca novel. Asyik! Sebuah memoar percintaan yang dikemas sebagai memoar otobiografi perjalanan hidup Rosihan Anwar. Disebut memoar karena tidak seluruhnya disampaikan lengkap, baik jalinan kisah percintaan maupun perjalanan hidup Rosihan Anwar. Hanya bagian-bagian tertentu yang disampaikan, yang paling diingat dan dipilih hanya yang ingin disampaikan kepada khalayak.
Seperti tamsil yang sering dia sampaikan secara lisan, ia menulis dalam air. Mengalir dan membiarkan diri terbuai arus. Dia tidak melawan derasnya arus, tetapi mengikuti arus, karena itu tulisan-tulisannya mengalir enak dibaca. Dilengkapi data serba detail, kelebihan ini dipuji oleh Jakob Oetama. ”Rosihan itu serba detail tidak umum- umum saja.” Jalinan kisahnya menyatu. Tidak saja berkisah tentang percintaan, tetapi juga lanskap momen- momen penting perjalanan negeri ini. Karena profesinya, karena inklinasinya, karena sosoknya yang ingin omni present (hadir dalam semua peristiwa), utamanya momen-momen penting kenegaraan. Dialah saksi sejarah negeri ini dengan jatuh- bangunnya, sejak sebelum merdeka di zaman penjajahan, di zaman merdeka, bahkan di zaman reformasi beberapa tahun terakhir. Rosihan dan Zuraida (Ida) ibarat cawan mosaik, menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah.
Tidak ada pembagian kaku atas memoar percintaan dan memoar Rosihan. Keduanya berkelindan satu sama lain, mengalir. Dimulai dari rumah di Jalan Ketapang yang dirampas NICA, berakhir dengan saat-saat sebelum meninggalnya. Ingatannya prima, keunggulan yang sampai sekarang dikagumi rekan-rekannya wartawan muda, membuat kisah percintaan dan memoar otobiografi ini menarik. Tidak saja sejarah pribadi, tetapi juga sejarah negeri ini.
Pertemuan pertama dengan buah hati selalu mengesan, yang kemudian dijalin dengan kisah standar tentang rumah tangga dan kehidupan bersama membangun keluarga. Rosihan dan Ida bertemu pertama kali di harian Asia Raya, awal April 1943. Bersama Halimah, Ida bekerja di bagian sekretariat redaksi yang tempat duduknya tidak jauh dari Soekardjo Wiryopranoto, Pemimpin Umum Asia Raya dan pemimpin Partai Indonesia Raya.
Rosihan kaget (hal 16) ketika dipanggil ”tuwan”, terjemahan kata meneer. Panggilan bung belum populer. Panggilan saudara dianggap bahasa buku. Rosihan memanggil Ida dengan sebutan saudara, bukan nona terjemahan juffrouw. Ada kekagokan, sesuatu yang umum dan manusiawi.
Seolah-olah serba kebetulan, termasuk Rosihan semula bercita-cita jadi jaksa kemudian beralih ke wartawan, pertemuan pertama di Asia Raya merupakan kisah pertama yang pilin-memilin dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi seolah-olah serba kebetulan. Membenarkan pernyataan Jakob Oetama, Rosihan itu manusia colourful. Karena tidak dibumbu basa-basi, apa adanya, romantika awal percintaannya menarik. Di antaranya, sehabis menghadiri pesta pernikahan Usmar Ismail dengan Mien (kakak Ida), Rosihan ajak Ida nonton film naik becak dengan kebaya lengkap (hal 21). Dalam kisah percintaan itu muncul nama-nama besar yang menyejarah di negeri ini, tidak hanya tokoh politik tapi juga budaya.
Apakah ranah pengembaraan Rosihan hanya di bidang politik dan budaya? Tidak, meskipun barangkali kedua bidang itulah yang menjadi inklinasi kuat minatnya. Yang jelas, bidang ekonomi jauh dari perhatiannya. Politik karena di masa itu merupakan persoalan yang tidak boleh tidak harus jadi bagian dari keseharian wartawan (eksistensi pers Indonesia awal lahir dari gua garba cita-cita kemerdekaan), sedangkan budaya bagian dari minat intrinsik Rosihan seperti dia tunjukkan dalam kegiatan-kegiatan kulturalnya kemudian.
Buku ini secara tidak langsung telah mengangkat sejumlah keteladanan. Keteladanan kerja keras, tidak mudah puas, kritis, dan senantiasa menggugat. Tidak saja upaya keras dalam merebut hati Ida, terutama kedua orangtuanya, tetapi juga sikap kerja dan semangatnya—yang terus menulis hingga akhir hayat. Keteladanan itu dikisahkan dalam memoar yang niscaya menjadi bahan belajar, tidak saja bagi cara kerja wartawan yang harus all out, tetapi juga sikap kerja omni present—yang bisa diterjemahkan dalam kehadiran fisik tetapi juga psikis dan nurani terhadap kondisi masyarakat dan negara.
Posisinya sebagai wartawan dalam arti sebagai penulis jauh lebih lama dibanding kariernya dalam memimpin media, baik di Asia Raya, Pedoman, maupun Siasat. Tetapi darma baktinya sebagai wartawan yang melebihi 75 tahun tercatat dalam sejarah, termasuk juga aktivitasnya sebagai guru wartawan maupun kegiatan di organisasi PWI dan juga perfilman.
Rosihan penuh warna, wartawan sejati, bersosok jenaka, yang membuat orang jengkel dan di saat lain kemudian merasa akrab. Dan itu membenarkan pernyataan Jakob dalam kata Pengantar, Rosihan ”mempresentasikan profesi jati diri wartawan sebagai panggilan (vocatio), bukan sekadar pekerjaan (job) atau karier (career).
Ya, wartawan tiga zaman itu kini sudah menemui sang ”belahan jiwa” yang pernah jadi istrinya lebih dari 63 tahun.
***
Memoar Tak Bersensor Mang Ayat
• Judul: 65>67: Catatan Acak-Acakan dan Catatan Apa Adanya
Sebagaimana judulnya, buku ini merupakan coretan rekaman berbagai hal. Ajip Rosidi, kakak Mang Ayat (meninggal 18 Februari 2006), sengaja menyajikan memoar ini persis seperti yang tertulis. Demi keotentikan dokumen, tulisan asli tanpa editan tetap dipertahankan, walaupun berpotensi membuat beberapa pihak kurang berkenan.
Salah satu tulisan yang menarik adalah cerita ketika Ayat mendapat tugas rahasia, konon dari R1. Ia diminta untuk menemukan sebuah tempat di Trowulan, di mana disebut-sebut dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca (1365) sebagai tempat Mahapatih Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa. Konon pula, R1 itu ingin menginap di wilayah Jawa Timur, namun gurunya berpesan bahwa R1 baru boleh menginap jika sudah dipastikan di mana Gajah Mada mengucapkan sumpah saktinya.
Ayat melaksanakan tugas tersebut, tapi kembali dengan tangan hampa. Padahal, ia sampai harus meminjam foto udara wilayah Trowulan untuk membandingkan uraian Prapanca mengenai ibu kota Majapahit dengan Trowulan dan foto udara. Akibatnya, menurut Ayat, hingga R1 itu lengser, beliau tak berani bermalam di wilayah Jawa Timur. Sering kali terlintas dalam benaknya, apakah lengsernya R1 itu ada kaitannya dengan kegagalan dirinya menemukan Wisma Panangkilan, tempat Gajah Mada mengucap sumpah.
***
Dinamika Keagamaan di Manado
• Judul: Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado
Manado adalah kota yang memiliki hubungan yang khas dengan agama Kristen. Gedung gereja banyak dijumpai nyaris di semua jalan utama maupun pelosok kota. Publikasi ini sendiri mencoba menyoroti dinamika keagamaan di Manado, dengan mengungkap perubahan sosial dan penggunaan ruang keagamaan di era 1919-1972.
Masa kolonial menjadi gerbang utama dan pusat penyebaran agama Kristen. Dinamika keagamaan ditandai oleh sibuknya usaha pengkristenan orang-orang Minahasa. Agama Kristen terlembaga dalam ”Gereja Negara” yang pengelolaannya dikontrol oleh pemerintah sehingga tidak bebas mengembangkan simbol-simbol agama.
Lain lagi dengan dinamika keagamaan pascakolonial. Meningkatnya aktivitas keagamaan mendorong semaraknya pendirian rumah ibadah dan fasilitas keagamaan untuk menggantikan simbol kolonial. Atribut kolonial diganti dengan simbol agama atau lokal, terutama bangunan gereja. Fungsi gereja juga menjadi ajang aktivitas sosial atau tempat pertemuan.
Maraknya bangunan gereja terjadi antara lain karena denominasi dalam Kristen berkembang pesat seiring dengan masuknya pekabar Injil dari berbagai aliran. Selain itu, pola penyebarannya yang tumbuh seiring dengan perluasan misi pendidikan dan kesehatan, seperti yang dilakukan Gereja Masehi Injili Minahasa atau GMIM pada 1966.