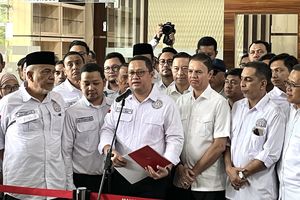Dari Trump hingga Duterte: Saat Data Bukan Lagi Segalanya
Pesan yang disampaikan beberapa pembicara tersebut begitu kuat dan jelas, “Selamat tinggal subjektivitas, abad ke-21 adalah era “Big Data”, penting untuk memiliki kemampuan mengolah berkwintal-kwintal byte data informasi
Benarkah itu?
Tahun lalu saat puncak pemilihan Presiden Amerika, saya berada di Houston, Texas. Saya menghabiskan waktu dengan keluarga Vidana, yakni dua bersaudara laki-laki keturunan Meksiko-Amerika yang tinggal di pinggiran kota yang kaya dengan minyaknya.
Kedua saudara yang menyukai senapan api ini merupakan pendukung keras Donald Trump meskipun mereka berdarah Latin. Ini membingungkan saya.
Mereka mendukung si rambut kuning jeruk yang bahkan telah mengancam untuk membangun tembok dan menendang keluar orang-orang seperti mereka!
Tetapi setelah saya menghabiskan beberapa hari bersama mereka, mengobrol sambil menikmati tacos di restoran Meksiko lokal, melihat-lihat toko senapan mereka, berbicara dengan orangtua, sepupu, kakek serta nenek mereka dan lainnya, saya mengerti mengapa mereka mendukung Trump.
Keputusasaan mereka akan perubahan itu tidak ditangkap oleh survei yang harusnya menilai kekecewaan mereka dari skala dari 1 sampai 10.
Pada hari pemungutan suara, The New York Times merilis sebuah prediksi bahwa kemungkinan Clinton akan menang adalah 85 persen. Setelah berpekan-pekan berbicara dengan masyarakat dari berbagai kalangan di seluruh Amerika Serikat, saya pun menjadi tidak begitu yakin.
Suatu malam, saat saya duduk di sebuah hotel area pedesaan di Michigan, yang menjadi pusat gelombang para pendukung Trump, saya tenggelam dengan perasaan bahwa mantan bintang acara televisi tersebut akan naik ke puncak.
Banyak kecemasan saya ketika ternyata dia berhasil melakukannya. Para pakar tercengang dan mungkin ada yang belum pulih dari kejadian tersebut.
Pada akhirnya, sifat naif akan ketergantungan pada data malah dapat mengecewakan kita. Jangan salah sangka. Data itu sebenarnya penting.
Semua fakta dan angka seperti pertumbuhan PDB, inflasi, tingkat pengangguran, dan nilai pendapatan adalah “tulang punggung” bagi sebagian analisis hebat.
Namun di dunia yang sudah ditenggelamkan oleh data, memahami angka-angka saja tidak cukup.
Facebook mengumpulkan informasi terkait setiap posting yang Anda suka, Google mencatat setiap pencarian yang Anda lakukan, dan Instagram merekam setiap foto yang Anda upload.
Kita yang meninggalkan kehidupan privasi kita dan membiarkan orang-orang mengetahui hal-hal kecil dalam hidup kita, yang terkadang tidak hanya untuk teman ataupun keluarga dekat.
Bahkan, data yang begitu banyak ini telah dibuat senyaman mungkin untuk dicari seperti yang telah dilakukan Apple dengan Siri, namun berapa biayanya?
Baru-baru ini, terungkap bahwa ada kebocoran informasi besar dari 46 juta pengguna ponsel di Malaysia, yang telah membuka informasi-informasi pribadi, seperti alamat rumah, nomor kartu identitas dan bahkan catatan medis.
Pada saat bersamaan, kita harus lebih berhati-hati dalam memuja data-data. Beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga survei telah membawa gelombang antusiasme “Big Data”, yang dapat menaikkan status seorang bintang rock ketika ikut dalam persaingan politik—dan seperti mendapatkan tamparan keras ketika prediksinya salah.
Banyak survei yang gagal melihat dominasi Trump, Brexit, dan lahirnya gerakan etno-nasionalis di seluruh Eropa.
Cathy O'Neil, seorang ahli matematika dari Harvard, dalam bukunya Weapons of Math Destruction, telah memperingatkan bahayanya “terlalu percaya” pada suatu data besar. Dia berpendapat bahwa "objektivitas" merupakan sebuah "trik pemasaran", yang menunjukkan bahwa algoritma yang kabur dan penuh asumsi yang salah, sebenarnya malah memperkuat sifat prasangka seorang manusia.
Terkadang, berpegang teguh pada sebuah data yang kita tahu malah dapat menjebak kita dalam sejarah. Lagi pula, tidak ada data untuk sebuah gagasan yang baru dan belum teruji.
Ini semua menunjukkan data bukanlah sebuah takdir.
Tetapi seharusnya kita tidak sepenuhnya buta ketika sedang mengikuti insting kita. Sebaliknya, pengetahuan manusia harus ditambah dengan sebuah informasi untuk melangkah ke depan.
Kita perlu menjadi seseorang yang memanfaatkan data sebagai bahan membuat keputusan, Tapi bukan sebagai orang yang dikendalikan data. Ini adalah dua hal yang berbeda.
Pada September lalu, sebuah survei dari lembaga penelitian Social Weather Stations (SWS) merilis turunnya peringkat kepercayaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte sebesar 15 poin.
Kelompok oposisi dan media setempat dengan cepat mengambil kesempatan ini dengan menggembar-gemborkan isu akhir dari "bulan madu" sang pemimpin kontroversial tersebut.
Saya sempat terbang ke Filipina dan berbincang-bincang dengan beberapa pendukung Duterte untuk melihat apa sebenarnya penyebab penurunan kepercayaan itu.
"Duterte telah membawa hasil yang nyata, dan hidup saya menjadi lebih baik dengan cara yang lebih baik juga sejak dia menjadi Presiden. Masyarakat dapat merasakannya," ujar Abad.
Beberapa hari setelah drilisnya survei SWS, studi lain dari lembaga saingan SWS yakni Pulse Asia menunjukkan bahwa dengan menggunakan margin error, penurunan peringkat kepercayaan presiden hanya 1 persen.
Ketika dihadapkan dengan data yang saling bertentangan maka tidak ada cara lain selain untuk terjun langsung ke lapangan.
“Iblis jahat” seperti ada di dalam setiap detil dan seringkali angka tidak dapat menangkap semua persepsi manusia yang sesungguhnya.
Di dalam survei, para pemilih enggan untuk mengungkapkan masalah yang ada di dalam hati mereka, dan mencoba mengungkapkan perasaan yang rumit tersebut menjadi jawaban yang lebih sederhana: Ya atau Tidak.
Jawaban antara "Ya" dan "Tidak" merupakan jawaban yang dibuat oleh para raja. Pada suatu hari nanti, data menjadi seperti sebuah kata dalam karya sastra yang perlu Anda tafsirkan.
Banyak ilmuwan di antara kita menginginkan sebuah dunia tanpa adanya prasangka, tapi kita tetap saja seorang manusia, yang berarti penuh dengan ketidakpastian.
Dan terkadang saya menggerutu karena ketidakrasionalan, kontradiksi dan kekacauan yang menjadi sifat dasar manusia. Namun pada akhirnya, saya tetap tidak akan mengubah apapun.
Asia Tenggara dan orang-orangnya adalah hal yang sangat menarik untuk ditunggu.
https://internasional.kompas.com/read/2017/11/28/22345581/dari-trump-hingga-duterte-saat-data-bukan-lagi-segalanya



























![[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin](https://asset.kompas.com/crops/CmFtWnU7cFk51oPm5v6fzCWRDMY=/0x0:2048x1365/177x117/data/photo/2020/02/29/5e5a19b09c689.jpg)